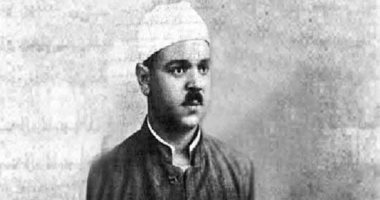1. Pendahuluan
Al-Qur’an adalah kitab suci yang diyakini umat Islam sebagai kalam Tuhan yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sepanjang sejarah Islam, Al-Qur’an telah menjadi objek kajian yang tak pernah habis dibahas dari berbagai pendekatan dan perspektif keilmuan. Salah satu pendekatan tafsir yang cukup revolusioner dalam sejarah penafsiran modern adalah metode tafsir sastrawi (al-tafsīr al-adabī). Pendekatan ini menawarkan sudut pandang baru dalam memahami teks suci dengan menjadikannya sebagai karya sastra Arab tertinggi yang memiliki struktur, gaya, dan estetika yang khas. Dalam konteks modern, pendekatan ini menjadi jembatan antara studi keagamaan dan kajian sastra klasik maupun kontemporer, serta menjawab kebutuhan masyarakat akademik yang semakin kompleks terhadap metode interpretasi yang segar dan kontekstual.
Tokoh sentral di balik lahirnya metode tafsir sastrawi adalah Amin al-Khulliy, seorang intelektual dan akademisi Mesir yang mengabdikan hidupnya untuk kajian Al-Qur’an dan bahasa Arab. Al-Khulliy tidak hanya melihat Al-Qur’an sebagai teks religius yang penuh muatan hukum, tetapi juga sebagai teks yang sangat kental dengan keindahan sastra. Dalam pandangannya, pendekatan yang mengabaikan aspek linguistik, retoris, dan keindahan bahasa dalam Al-Qur’an akan membuat pesan ilahiah yang terkandung di dalamnya menjadi kaku dan kehilangan daya hidup. Oleh karena itu, al-Khulliy menekankan bahwa studi Al-Qur’an tidak bisa dilepaskan dari pendekatan sastra sebagai pintu masuk utama dalam memahami pesan-pesan yang dikandung oleh ayat-ayat suci tersebut.
Pemikiran Amin al-Khulliy muncul pada masa yang menantang, di mana perdebatan antara kaum modernis dan tradisionalis sedang memanas di dunia Islam. Kehadiran metode tafsir sastrawi yang ia gagas bisa dikatakan sebagai sintesis dari dua kutub ini: ia memelihara keotentikan teks dan semangat keilmuan klasik, namun sekaligus membuka ruang untuk pendekatan baru yang lebih ilmiah, kritis, dan kontekstual. Gagasannya bukan semata inovasi akademis, tetapi juga merupakan respons terhadap stagnasi penafsiran yang menurutnya telah dikungkung oleh pembacaan dogmatis dan ideologis yang sempit. Dengan demikian, metode tafsir sastrawi menjadi bentuk perlawanan terhadap stagnasi tersebut dan menawarkan pembacaan Qur’an yang lebih segar dan dinamis.
Pendekatan tafsir sastrawi tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode tafsir klasik seperti tafsir bi al-ma’tsur atau tafsir fiqih, melainkan sebagai pelengkap dan pelurusan terhadap pendekatan-pendekatan yang terlalu membebani teks dengan asumsi-asumsi luar yang terkadang tidak sesuai dengan konteks linguistik dan sastra Qur’an. Melalui pendekatan ini, teks suci dibaca dengan memperhatikan struktur retorisnya, latar historis sosialnya, dan keterkaitannya satu sama lain dalam konteks keseluruhan Qur’an. Ini memberikan ruang untuk eksplorasi makna yang lebih dalam, sekaligus membuka peluang bagi penafsiran yang lebih humanistik, kontekstual, dan relevan dengan persoalan kontemporer.
Relevansi tafsir sastrawi pada masa kini semakin dirasakan ketika dunia akademik Islam mulai terbuka terhadap pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Gagasan al-Khulliy memberikan kontribusi besar bagi kajian tafsir di universitas-universitas Islam, baik di Timur Tengah maupun Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pemikirannya telah melahirkan banyak pengikut dan murid, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Ahmad Khalafallah dan Aisyah Abdurrahman (Bint al-Syathi’), yang meneruskan metode ini dalam bentuk karya tafsir yang lebih aplikatif. Melalui pendekatan ini pula, Qur’an tidak hanya menjadi kitab hukum atau akidah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi intelektual dan estetika dalam konteks peradaban yang luas.
2. Biografi Singkat
Amin al-Khulliy lahir pada 1 Mei 1895 di Provinsi Menoufia, Mesir, dari keluarga yang sangat religius dan berpendidikan tinggi. Sejak kecil ia telah belajar dan menghafal Al-Qur’an, serta mendalami ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, sharaf, balaghah, dan ushul fikih di bawah bimbingan ayahnya yang merupakan lulusan al-Azhar. Latar belakang keluarga yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam membentuk dasar intelektual yang kokoh dalam dirinya. Tidak heran jika sejak usia belia, al-Khulliy telah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang bahasa Arab dan tafsir.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, Amin al-Khulliy melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar, pusat studi Islam tertua dan paling prestisius di dunia Islam. Di sana ia mendalami berbagai ilmu keislaman klasik dan juga memperluas cakrawala keilmuan dengan mempelajari ilmu logika, filsafat, dan sastra Arab klasik. Minatnya terhadap bahasa Arab membawanya untuk memperdalam analisis linguistik dan estetika sastra Arab. Di al-Azhar pula, ia mulai mengembangkan gagasan bahwa teks suci Al-Qur’an tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melihat keindahan dan kekuatan bahasanya sebagai produk linguistik Arab yang unggul.
Pada awal kariernya, Amin al-Khulliy sempat ditugaskan sebagai utusan intelektual Mesir ke berbagai negara seperti Italia dan Jerman pada tahun 1920-an. Pengalaman ini memperkaya wawasannya dan mempertemukannya dengan berbagai pemikiran modern dan pendekatan akademik Barat terhadap teks-teks kuno. Ia pun mulai terinspirasi untuk menerapkan metode ilmiah dan pendekatan sastra modern terhadap studi Al-Qur’an. Ketika kembali ke Mesir, ia aktif mengajar di Fakultas Sastra Universitas Kairo dan kemudian diangkat sebagai dekan fakultas tersebut. Di sinilah ia mulai menyebarkan gagasannya tentang pentingnya pendekatan sastra dalam memahami Al-Qur’an.
Al-Khulliy dikenal sebagai akademisi yang sangat kritis dan reformis. Ia banyak menulis artikel dan karya ilmiah tentang hubungan antara sastra Arab dan Al-Qur’an, serta mengkritik metode tafsir klasik yang dianggapnya terlalu literal dan kurang memperhatikan aspek sastra. Dalam salah satu tulisannya yang terkenal, ia menyatakan bahwa “tafsir harus membebaskan diri dari belenggu ideologi dan mendekati teks secara ilmiah dan estetis.” Pandangan ini mengundang kontroversi, terutama dari kalangan ulama konservatif yang menganggap pendekatan semacam itu merendahkan nilai wahyu. Namun, bagi al-Khulliy, pendekatan ilmiah justru mengangkat kemuliaan Al-Qur’an sebagai teks yang luar biasa.
Pada tahun 1947, al-Khulliy menjadi sorotan publik setelah membimbing disertasi Muhammad Ahmad Khalafallah yang berjudul Al-Fann al-Qasasi fi al-Qur’an al-Karim. Disertasi ini menyatakan bahwa cerita-cerita dalam Al-Qur’an harus dipahami sebagai karya seni dan sastra, bukan semata-mata sebagai catatan sejarah. Gagasan ini dianggap sangat radikal dan menimbulkan perdebatan panas di lingkungan akademik dan keagamaan Mesir. Namun, al-Khulliy tetap teguh pada pendiriannya dan membela disertasi tersebut sebagai bagian dari pendekatan ilmiah terhadap teks suci. Ia percaya bahwa Al-Qur’an akan tetap mulia meskipun dipelajari dengan pendekatan modern, bahkan akan semakin menunjukkan keunggulannya.
3. Latar Belakang Pemikiran dan Konteks Historis
Pemikiran Amin al-Khulliy tidak muncul dalam ruang hampa. Ia merupakan bagian dari gerakan intelektual besar di Mesir pada awal abad ke-20 yang mengusung modernisme Islam, khususnya dalam lingkaran pembaruan yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Gerakan ini mendorong reinterpretasi Islam yang rasional, terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern, serta menolak taqlid. Dalam lingkungan seperti inilah al-Khulliy mengembangkan gagasan pembaruan dalam studi tafsir. Ia melihat bahwa selama berabad-abad tafsir Al-Qur’an telah terjebak dalam pola-pola pemaknaan yang statis, sempit, dan penuh kepentingan ideologis—baik dari madzhab fikih, teologi, maupun politik. Oleh karena itu, dibutuhkan metode baru yang dapat menghidupkan kembali Al-Qur’an sebagai teks yang terus relevan sepanjang zaman.
Selain pengaruh dari pembaruan Islam, Amin al-Khulliy juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan studi sastra Arab modern dan studi orientalis Barat terhadap teks-teks klasik. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pemikiran al-Khulliy adalah Taha Husayn, seorang cendekiawan Mesir yang mendalami studi sastra di Prancis dan memperkenalkan metode kritis Barat ke dalam studi sastra Arab. Husayn mendorong pembacaan teks-teks Arab, termasuk Al-Qur’an, dengan pendekatan sastra yang ilmiah dan tidak dogmatis. Al-Khulliy, yang merupakan salah satu murid dan kolega intelektual Husayn, menerjemahkan semangat ini ke dalam studi Al-Qur’an, dengan keyakinan bahwa teks suci tersebut juga harus dipahami sebagai teks sastra yang hidup, bukan hanya sebagai kitab hukum dan teologi.
Konflik ideologis pada masa itu, antara modernis dan tradisionalis, juga memberi ruang bagi al-Khulliy untuk mengkritisi pola pikir keagamaan yang stagnan. Menurutnya, banyak metode tafsir yang dikembangkan sebelumnya terlalu membebani teks dengan asumsi-asumsi teologis, sehingga menutupi makna sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Al-Qur’an. Ia menilai bahwa pendekatan hukum (fiqih) dan dogmatisme teologis telah menjadikan Al-Qur’an sekadar ladang justifikasi, bukan sumber nilai estetika, moral, dan humanisme. Oleh sebab itu, ia merasa perlu untuk mendekati Al-Qur’an dari sisi yang lebih manusiawi, dengan menjadikannya sebagai karya seni dan sastra yang hidup dalam kesadaran manusia Arab.
Bersamaan dengan itu, muncul pula kebutuhan untuk membangun jembatan antara tradisi Islam dan dunia akademik modern. Amin al-Khulliy menyadari bahwa jika umat Islam ingin mempertahankan relevansi Al-Qur’an dalam era modern, maka mereka harus mampu membaca dan menafsirkan Al-Qur’an dengan bahasa dan pendekatan yang dimengerti oleh manusia modern. Oleh karena itu, ia mencoba membumikan metode tafsir yang lebih objektif, metodologis, dan sistematis—yang tidak hanya bisa diterima oleh kalangan tradisional, tetapi juga dapat diuji secara akademik di dunia ilmiah. Ini menjadikan metode tafsir sastrawi bukan sekadar pendekatan alternatif, tetapi sebuah proyek intelektual besar yang berakar kuat pada sejarah dan kebutuhan zaman.
Salah satu karakter menonjol dari pemikiran al-Khulliy adalah keberaniannya untuk merombak tradisi yang dianggap sudah mapan. Dalam banyak tulisannya, ia tidak segan-segan mengkritik para mufassir terdahulu yang terlalu tekstual atau mengandalkan hadis semata dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Baginya, hadis memang penting, namun tidak boleh menutup ruang interpretasi baru yang lebih kreatif dan kontekstual. Pemikiran ini menjadi bagian penting dari pembaruan metode tafsir kontemporer yang terus berkembang hingga hari ini. Melalui pendekatan sastra, al-Khulliy membuktikan bahwa Al-Qur’an bisa dipahami secara lebih mendalam, rasional, dan menyentuh sisi kemanusiaan.
4. Konsep “Al-Qur’an: Kitab Sastra Arab Terbesar”
Amin al-Khulliy berangkat dari asumsi mendasar bahwa Al-Qur’an adalah karya sastra Arab terbesar. Dalam pandangannya, keagungan Al-Qur’an tidak hanya terletak pada muatan spiritual atau hukum-hukumnya, tetapi juga dalam struktur bahasanya yang luar biasa indah dan kompleks. Al-Qur’an menggunakan gaya bahasa yang khas, metafora yang kuat, struktur naratif yang kaya, serta pilihan kata yang sangat tepat. Semua ini, menurut al-Khulliy, menjadikan Al-Qur’an sebagai karya sastra puncak dalam peradaban Arab. Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang mengabaikan aspek sastra hanya akan menangkap sebagian kecil dari pesan ilahiah yang terkandung di dalamnya.
Konsep “kitab sastra Arab terbesar” juga mengandung konsekuensi bahwa Al-Qur’an harus diperlakukan seperti teks sastra lainnya dalam hal metodologi pembacaan. Ini berarti bahwa alat-alat kritis dalam analisis sastra Arab klasik dan modern, seperti balaghah, nahwu, dan ilmu bayan, harus digunakan secara maksimal untuk menggali makna Al-Qur’an. Al-Khulliy mengajak para mufassir untuk tidak hanya fokus pada makna literal ayat, tetapi juga menggali makna implisit, simbolik, dan retoris yang terkandung dalam setiap kata dan susunan ayat. Dengan pendekatan ini, Al-Qur’an tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi juga menjadi teks yang menginspirasi keindahan, refleksi moral, dan transformasi sosial.
Di sisi lain, pandangan al-Khulliy ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan konservatif. Mereka menganggap bahwa menyamakan Al-Qur’an dengan karya sastra biasa bisa merendahkan statusnya sebagai wahyu Tuhan. Namun, al-Khulliy dengan tegas membantah anggapan tersebut. Menurutnya, justru dengan memahami Al-Qur’an sebagai karya sastra ilahiah, umat Islam akan semakin memahami keunikan dan kekuatan mukjizat Al-Qur’an. Ia tidak menolak bahwa Al-Qur’an adalah wahyu, namun menekankan bahwa wahyu tersebut diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki struktur dan keindahan tersendiri, sehingga perlu dianalisis dengan pendekatan linguistik dan sastra.
Lebih jauh, al-Khulliy juga menekankan bahwa dengan pendekatan ini, pembaca bisa lebih memahami konteks sosial dan psikologis masyarakat Arab saat ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan. Sastra selalu mencerminkan realitas sosial tempat ia muncul, begitu pula dengan Al-Qur’an. Dengan memahami Al-Qur’an sebagai teks sastra, maka pembaca dapat melihat bagaimana wahyu merespons realitas sosial, budaya, dan bahkan psikologis masyarakat Arab pada masa kenabian. Hal ini memberikan kedalaman dalam memahami maksud ayat, serta membuka ruang untuk pemaknaan baru yang sesuai dengan konteks kekinian tanpa kehilangan ruh teks aslinya.
5. Prinsip Dasar Metode Tafsir Sastrawi Amin al-Khulliy
Amin al-Khulliy mengembangkan metode tafsir sastrawi dengan fondasi ilmiah yang kuat. Ia membagi pendekatannya ke dalam dua tahap utama: dirasah khārijiyyah (kajian eksternal) dan dirasah dākhiliyyah (kajian internal). Tahap pertama, dirasah khārijiyyah, berfungsi untuk memahami konteks sosial, sejarah, budaya, dan geografis saat ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan. Dalam tahap ini, mufassir dituntut untuk menggali informasi dari sumber-sumber sejarah Islam awal, seperti sirah nabawiyah, sebab-sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), serta kondisi linguistik dan budaya masyarakat Arab masa itu. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan dalam memahami makna ayat karena diabaikannya konteks asal-usulnya.
Tahap kedua adalah dirasah dākhiliyyah, yaitu analisis internal terhadap struktur teks Al-Qur’an itu sendiri. Dalam tahap ini, al-Khulliy mendorong penggunaan pendekatan linguistik dan retoris secara intensif. Artinya, mufassir harus memperhatikan susunan kalimat, pilihan diksi, gaya bahasa, pengulangan, penekanan, serta hubungan antar ayat dan surat. Dengan pendekatan ini, teks Al-Qur’an dibaca seperti puisi atau karya sastra tinggi, yang setiap elemen bahasanya menyimpan makna yang kaya dan mendalam. Ini menjadikan penafsiran lebih variatif, dinamis, dan mampu mengakomodasi keunikan gaya Qur’an yang tak dimiliki oleh teks lainnya.
Al-Khulliy juga menekankan pentingnya pendekatan tematik (mawḍūʿī) dalam menafsirkan Al-Qur’an. Ia mengkritik tafsir klasik yang terlalu atomistik—membaca ayat demi ayat secara terpisah—sehingga seringkali gagal menangkap pesan utuh dari suatu tema. Sebaliknya, pendekatan tematik mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, misalnya keadilan, kasih sayang, atau keesaan Tuhan, kemudian dianalisis secara komprehensif dari berbagai sisi bahasa, retorika, dan konteksnya. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap pesan-pesan Qur’ani yang terkandung dalam berbagai bagian kitab suci.
Selain itu, metode al-Khulliy juga menggunakan tartīb nuzūlī (urutan kronologis turunnya wahyu) sebagai dasar pembacaan. Dengan cara ini, pembaca bisa memahami perkembangan wacana dan misi Qur’an secara bertahap, seiring dengan perubahan kondisi sosial dan psikologis umat Islam awal. Pendekatan ini menyoroti bagaimana Qur’an merespons berbagai tantangan secara evolutif, bukan hanya secara dogmatis. Oleh karena itu, memahami urutan turunnya wahyu menjadi penting untuk mengerti semangat dan arah dakwah Qur’an. Ini memperkaya tafsir dengan dimensi sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pendekatan-pendekatan tradisional.
6. Implementasi Gagasan: Kritikus dan Pengikut
Metode tafsir sastrawi yang dirumuskan Amin al-Khulliy tidak berhenti pada tataran gagasan. Ia berhasil mewariskan metode ini kepada sejumlah muridnya yang kemudian dikenal luas dalam dunia keilmuan Islam, terutama di bidang tafsir. Salah satu murid terpenting al-Khulliy adalah Muhammad Ahmad Khalafallah, yang menulis disertasi kontroversial berjudul al-Fann al-Qashasī fī al-Qur’ān al-Karīm (Seni Bercerita dalam Al-Qur’an). Dalam karya ini, Khalafallah memandang bahwa cerita-cerita dalam Al-Qur’an tidak semata sebagai laporan sejarah faktual, melainkan sebagai representasi artistik yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan spiritual. Ia menyatakan bahwa nilai kebenaran cerita Qur’ani terletak pada maknanya, bukan pada detail historisnya. Gagasan ini langsung mengundang badai kritik dari kalangan ulama konservatif dan menyebabkan ia ditolak promosi doktoralnya di Universitas Kairo pada tahun 1947.
Namun, al-Khulliy tetap mendukung Khalafallah dan berdiri sebagai pembimbing yang membela kebebasan akademik dan pendekatan ilmiah terhadap studi Al-Qur’an. Ia menilai bahwa tuduhan terhadap Khalafallah sebagai penista agama adalah bentuk kemunduran berpikir. Bagi al-Khulliy, yang lebih penting adalah membangun tradisi berpikir kritis dan ilmiah dalam memahami wahyu. Disertasi Khalafallah meskipun ditolak secara resmi, tetap diterbitkan dan menjadi salah satu rujukan penting dalam studi tafsir modern. Melalui peristiwa ini, metode tafsir sastrawi memperoleh pijakan akademik yang lebih kokoh, dan membuka ruang dialog antara ilmu sastra dan studi keislaman yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri.
Selain Khalafallah, pengikut terpenting lainnya adalah Aisyah Abdurrahman, atau lebih dikenal dengan nama pena Bint al-Syathi’. Ia adalah istri al-Khulliy sekaligus salah satu cendekiawati muslim paling berpengaruh di abad ke-20. Ia menulis karya monumental al-Tafsīr al-Bayānī li al-Qur’ān al-Karīm, yang secara sistematis menerapkan pendekatan sastrawi terhadap Al-Qur’an. Karya ini banyak menekankan analisis gaya bahasa, retorika, struktur naratif, dan makna simbolik dari ayat-ayat Qur’an, terutama pada surah-surah pendek di Juz Amma. Ia memelopori penggunaan gaya tafsir yang lebih puitis, mengedepankan nuansa makna dan estetika, tanpa melepaskan tanggung jawab teologisnya sebagai muslim.
Penerapan metode tafsir sastrawi oleh para pengikut al-Khulliy menjadikan pendekatan ini semakin populer, terutama di lingkungan akademik. Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin, juga mengambil inspirasi dari pendekatan ini dalam bukunya al-Taswīr al-Fannī fī al-Qur’ān, yang mengkaji simbolisme dan gambaran artistik dalam teks Qur’an. Meski Qutb kemudian lebih dikenal karena pendekatan ideologis-politiknya dalam Fi Zilal al-Qur’an, pengaruh awal metode sastrawi dalam karya-karyanya cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa metode al-Khulliy telah menjangkau berbagai spektrum pemikiran Islam, dari yang liberal hingga konservatif, selama digunakan dengan semangat akademik dan tanggung jawab ilmiah.
Meskipun demikian, penerimaan terhadap metode tafsir sastrawi tidak selalu positif. Banyak kalangan tradisionalis dan salafi yang menilai bahwa pendekatan ini mengandung risiko menurunkan status wahyu menjadi sekadar teks sastra. Mereka khawatir bahwa pendekatan ini akan membuka pintu bagi relativisme makna dan interpretasi bebas yang bisa merusak otoritas teks suci. Akan tetapi, para pendukung al-Khulliy menegaskan bahwa metode ini justru bertujuan melestarikan nilai-nilai Al-Qur’an dengan cara yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi mereka, tafsir sastrawi bukan bentuk pelecehan terhadap Qur’an, melainkan sarana untuk menggali kedalaman makna yang selama ini tersembunyi.
7. Dampak Metodologis pada Studi Tafsir Kontemporer
Dampak dari metode tafsir sastrawi Amin al-Khulliy sangat signifikan terhadap perkembangan studi tafsir di era modern. Di dunia akademik, pendekatan ini telah membuka jalan bagi integrasi ilmu-ilmu kebahasaan dan kesusastraan dalam studi Al-Qur’an yang sebelumnya didominasi oleh ilmu tafsir klasik. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah kajian akademik yang menggunakan analisis linguistik, struktural, dan semiotik dalam memahami ayat-ayat Qur’an. Bahkan dalam disertasi dan tesis di berbagai universitas Islam di dunia, pendekatan ini semakin populer karena menawarkan cara pembacaan yang lebih ilmiah, netral, dan kontekstual.
Salah satu dampak besar metode ini adalah terbukanya ruang untuk pendekatan interdisipliner. Studi tafsir kini tak hanya melibatkan ilmu tafsir dan hadis, tetapi juga linguistik, semiotika, sosiologi, psikologi, bahkan filsafat hermeneutika. Pemikiran Amin al-Khulliy menjadi titik tolak bagi pemikir seperti Nasr Hamid Abu Zayd, yang kemudian mengembangkan teori hermeneutika Qur’an yang sangat progresif. Meskipun Abu Zayd mengembangkan pendekatan yang lebih radikal, ia secara eksplisit mengakui bahwa inspirasinya datang dari metode tafsir sastrawi yang dikembangkan al-Khulliy. Dengan demikian, al-Khulliy bisa disebut sebagai bapak hermeneutika Qur’an modern dalam tradisi pemikiran Islam kontemporer.
Di Indonesia sendiri, metode tafsir sastrawi cukup banyak digunakan oleh para sarjana muda dan dosen di perguruan tinggi Islam. Kajian ini mendapat tempat di fakultas-fakultas ushuluddin dan adab, serta diterapkan dalam studi ayat-ayat tematik. Banyak jurnal ilmiah bereputasi yang menerbitkan kajian Al-Qur’an dengan pendekatan sastra, baik dalam konteks kebahasaan maupun sosiologis. Misalnya, penelitian tafsir tematik atas ayat puasa dalam konteks psikologi masyarakat modern menggunakan pendekatan al-Khulliy untuk memahami struktur dan gaya ayat serta dampaknya terhadap perilaku umat Islam.
Namun, seiring dengan semakin luasnya penerimaan terhadap metode ini, muncul pula tantangan baru. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa pendekatan sastra tidak jatuh pada pembacaan sekuler atau menghilangkan dimensi spiritual teks Qur’an. Karena itu, para pengikut metode al-Khulliy juga terus mengembangkan pendekatan yang seimbang antara kedalaman estetika dan kekuatan spiritual Al-Qur’an. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan bayani, yaitu metode pembacaan teks yang menekankan kejelasan, argumentasi, dan struktur wacana, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.
8. Kelebihan dan Keterbatasan Pendekatan Sastrawi
Pendekatan tafsir sastrawi memiliki banyak kelebihan yang membuatnya relevan dan sangat dibutuhkan dalam konteks akademik maupun sosial keagamaan modern. Pertama, pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pembaca untuk menggali makna Qur’an dari sisi estetik dan linguistik yang selama ini kurang diperhatikan. Dengan memahami struktur sastra dalam Qur’an, pembaca akan melihat keindahan dan kedalaman pesan wahyu secara lebih utuh. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Qur’an memang bukan sembarang teks, melainkan karya ilahi yang memiliki daya pikat estetik yang tinggi.
Kedua, pendekatan ini juga relevan dengan metode ilmiah modern. Ia membuka ruang untuk diskusi kritis, komparatif, dan interdisipliner. Ini membuat studi Al-Qur’an tidak lagi eksklusif hanya bagi ulama klasik, tetapi bisa dikaji oleh akademisi lintas disiplin, baik muslim maupun non-muslim. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi jembatan dialog antarbudaya dan antaragama dalam memahami pesan Qur’an. Ini sangat penting di tengah masyarakat global saat ini yang membutuhkan pendekatan inklusif dan humanistik dalam memahami teks keagamaan.
Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini bisa menjadikan Qur’an sebagai teks sastra biasa yang bisa ditafsirkan sebebas-bebasnya. Dalam kasus ekstrem, ini bisa membuka pintu relativisme yang menafikan otoritas wahyu. Karena itu, pendekatan ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab akademik yang tinggi. Para mufassir modern yang menggunakan metode ini harus tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan spiritualitas Qur’an sebagai kitab suci, bukan sekadar teks budaya.
Kritik lain datang dari sisi praktis. Karena pendekatan ini membutuhkan keahlian dalam linguistik, retorika, dan sastra Arab, maka tidak semua orang bisa menerapkannya dengan benar. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang serius agar metode ini tidak disalahgunakan atau dipahami secara setengah-setengah. Untuk itu, pengembangan kurikulum studi Qur’an di universitas harus memasukkan analisis sastra sebagai bagian dari pendidikan tafsir, sehingga metode ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi mufassir masa depan.
9. Studi Kasus: Tafsir Sastrawi atas Ayat Puasa
Salah satu penerapan metode tafsir sastrawi yang menarik adalah pada ayat-ayat tentang puasa dalam surah al-Baqarah (2:183–187). Dalam ayat ini, Al-Qur’an menyampaikan perintah puasa dengan gaya bahasa yang lembut, simbolik, dan naratif. Misalnya, frase “kutiba ‘alaykum al-shiyām” (diwajibkan atas kamu berpuasa) disampaikan dengan struktur pasif yang memberikan nuansa empatik, bukan perintah kasar. Pendekatan sastrawi membaca struktur ini sebagai bentuk perhatian Tuhan kepada manusia, bukan semata perintah legalistik. Hal ini berbeda dari pendekatan fikih yang lebih berfokus pada hukum dan syarat teknis puasa.
Penelitian dari UIN Sunan Kalijaga menggunakan metode tafsir sastrawi untuk mengkaji bagaimana gaya bahasa ayat-ayat puasa mempengaruhi psikologi umat Islam yang menjalankannya. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan ini bisa membangkitkan makna spiritual dan moral puasa secara lebih mendalam. Misalnya, frase “la‘allakum tattaqūn” tidak hanya bermakna “agar kamu bertakwa”, tetapi juga menjadi bentuk harapan dan kelembutan Tuhan terhadap umat-Nya. Ini memperlihatkan aspek humanistik dan estetik dari perintah puasa yang jarang terlihat jika dibaca hanya dari sisi hukum.
10. Kesimpulan
Amin al-Khulliy adalah pelopor metode tafsir sastrawi yang membawa angin segar dalam studi Al-Qur’an modern. Melalui pendekatan ini, ia menjembatani antara nilai wahyu dengan kaidah sastra dan ilmu linguistik modern. Gagasan-gagasannya telah menginspirasi generasi cendekiawan berikutnya dan membuka ruang tafsir yang lebih hidup, estetik, dan kontekstual. Metode ini bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga memberikan alternatif tafsir yang relevan dengan masyarakat modern yang haus akan pendekatan religius yang ramah, reflektif, dan ilmiah (Mohammad Nor Ichwan).